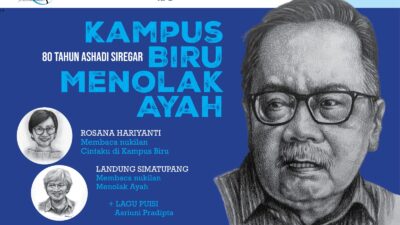bernasnews — Sangat penting untuk merenungkan momen nasional kita Hari Kebangkitan Nasional, agar tak sekedar seremoni apalagi terendam dalam rutinitas upacara belaka tanpa makna di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Republik Indonesia kita, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara terpadat keempat, telah menetapkan agenda yang berani, Visi Indonesia Emas 2045.
Peta jalan tersebut bercita-cita untuk mengubah negara ini menjadi ekonomi yang berdaulat, maju, adil, dan berkelanjutan pada tahun 2045, bertepatan dengan peringatan seratus tahun kemerdekaannya. Namun, tantangan internal yang sudah berlangsung lama mengancam untuk menggagalkan lintasan ini perwujudan visi ini. Di antara yang paling berbahaya adalah premanisme dan korupsi sistemik atau bahkan sustainable corruption phenomenon dimana para pelaku dan lingkungannya berkelit berkelindan bak lingkaran setan yang tiada ketahuan ujung pangkal untuk diputus. Fenomena ini mengakar dalam dan saling memperkuat yang mengikis kapasitas negara, mendistorsi fungsi pasar, dan melanggengkan ketimpangan.
Sementara premanisme—yang biasanya diterjemahkan sebagai gangsterisme tingkat jalanan atau orang kuat lokal yang koersif—sering kali diperlakukan sebagai masalah keamanan lokal, keterikatan dan normalisasi politiknya menuntut analisis yang lebih mendalam. Demikian pula, korupsi di Indonesia tidak lagi bersifat episodik; korupsi sistemik, tertanam dalam struktur kelembagaan, dan difasilitasi oleh budaya impunitas. Bersama-sama, isu-isu ini membentuk ekonomi politik disfungsi yang melemahkan janji-janji pembangunan.
Di bawah Orde Baru Suharto dulu, kelompok preman seperti Pemuda Pancasila memperoleh peran semi-sah, bertindak sebagai perpanjangan kekuasaan negara yang menggunakan kekerasan sambil mengonsolidasikan kendali politik lokal (Ryter, 2001). Pada periode pasca-Reformasi, premanisme tidak bubar; ia beradaptasi secara jenial dan fleksibel dalam beragam corak dan wujudnya. Banyak kelompok menjadi organisasi massa terdaftar (ormas), terlibat dalam kampanye politik, keadilan main hakim sendiri, dan pemerasan dengan kedok hukum.
Premanisme masa kini tidak lagi terbatas pada ruang-ruang yang terpinggirkan. Beberapa pemimpin preman telah menjadi anggota parlemen atau birokrat lokal. Pelembagaan paksaan dimungkinkan oleh penegakan hukum yang lemah, korupsi peradilan, dan politik klientelis (Hadiz, 2017). Metamorfosis ini telah mengaburkan batas antara pemerintahan formal dan usaha kriminal, menormalkan kekerasan sebagai alat politik.
Ini adalah fakta yang ironis: Konvergensi premanisme dan korupsi menciptakan lingkaran setan. Kelompok preman menyediakan kekuatan bagi para pelaku korup untuk mengintimidasi lawan, memanipulasi pemilu, atau menegakkan kontrak ilegal. Sebagai imbalannya, para pelaku preman memperoleh perlindungan politik, akses ke kontrak, dan impunitas (Mietzner, 2018). Kemitraan informal ini menyabotase lembaga hukum dan menumbuhkan budaya ketakutan. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia pernah dipuji sebagai model global, revisi terkini terhadap mandat dan struktur kepemimpinannya telah mengurangi independensinya. Anggarannya untuk tahun 2023 hanya 0,04% dari belanja nasional, yang sangat membatasi kapasitas operasionalnya (ISEAS, 2024).
Penegakan hukum yang dipolitisasi semakin melemahkan pencegahan. Korupsi tumbuh subur di mana mekanisme akuntabilitas diabaikan atau dikuasai. Hal ini terbukti di daerah-daerah yang terdesentralisasi di mana elit politik mengendalikan pengadaan, perizinan, dan layanan publik melalui jaringan yang tidak transparan. Fragmentasi semacam itu memungkinkan korupsi beradaptasi dan bermutasi, sehingga merusak segala upaya reformasi dari atas ke bawah.
Proliferasi premanisme dan korupsi secara bersamaan memperburuk ketimpangan. Pengusaha kecil menghadapi pemerasan; dana publik disedot; dan warga menjadi sinis tentang keterlibatan masyarakat. Di daerah-daerah yang terpinggirkan, kelompok preman sering kali menggantikan fungsi negara yang tidak ada, yang selanjutnya mendelegitimasi pemerintahan formal. Hasil akhirnya adalah stagnasi pembangunan, terutama dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Janji Indonesia Emas pada tahun 2045 memang menginspirasi, tetapi harus didasarkan pada realisme. Premanisme dan korupsi bukanlah masalah sampingan; keduanya merupakan kendala sistemik yang berakar pada ekonomi politik Indonesia. Mengatasinya tidak hanya membutuhkan solusi teknis tetapi juga keberanian politik dan mobilisasi masyarakat. Baru pada saat itulah cita-cita tahun 1945 dapat ditebus oleh kenyataan tahun 2045.
Ada beberapa agenda penting yang harus dilaksanakan: pertama, kewaspadaan publik merupakan pencegah yang krusial. Memperkuat pendidikan kewarganegaraan, melindungi whistleblower, dan memungkinkan jurnalisme investigasi dapat mengungkap jaringan kolusi. Platform digital juga menawarkan alat untuk pemantauan anggaran dan layanan publik secara crowdsourced.
Kedua, Indonesia perlu memulihkan independensi dan kapasitas lembaga antikorupsi. Ini termasuk membatalkan pembatalan legislatif baru-baru ini, memperluas kewenangan yurisdiksi, dan melindungi penunjukan kepemimpinan dari pengaruh politik. Lembaga penegak hukum harus menjalani reformasi struktural untuk melepaskan diri dari hubungan patron-klien. Ini melibatkan rekrutmen berbasis prestasi, audit kinerja, dan komisi peradilan independen untuk mengawasi pelanggaran integritas.
Semoga Hari Kebangkitan Nasional—hari penting bagi bangsa ini, di mana para pejabat membaca puisi, para siswa berdiri tegak menyanyikan lagu wajib, dan masyarakat menonton parade sambil bertanya-tanya,”bangkit dari apa, menuju ke mana?”. (G. Teguh Santoso, Konsultan Pendidikan dan Penulis Lepas)